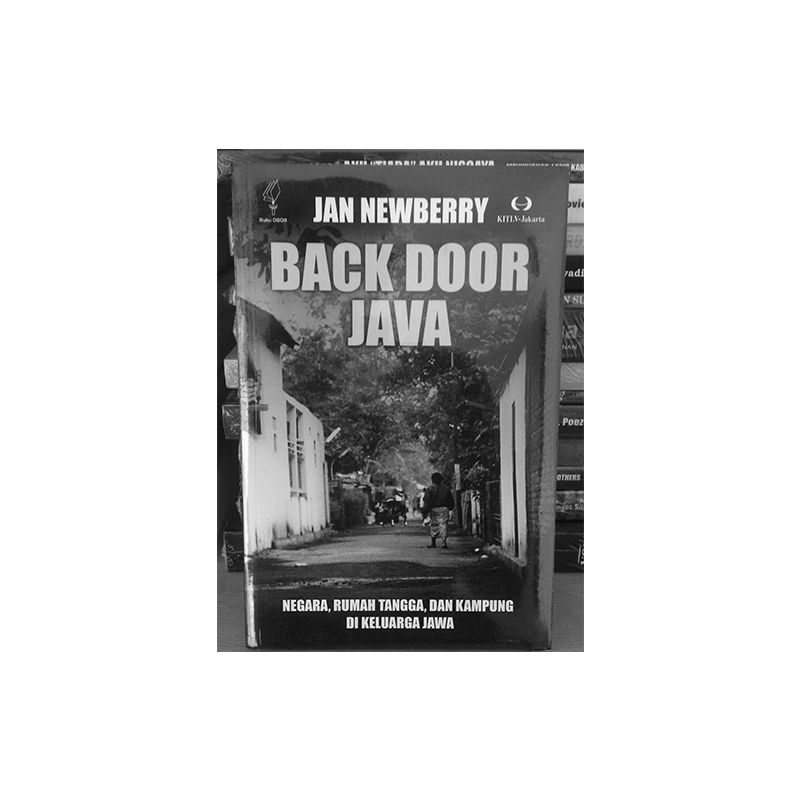Jan Newberry, seorang etnograf dari Universitas Lethbridge, Kanada pada tahun 2013 menulis sebuah buku yang menarik berjudul “Back Door Java” yang mengulas risetnya di Yogyakarta tentang “pintu belakang” yang menjadi ciri rumah-rumah masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta. Apa maksud dari pintu belakang itu? Kira-kira pertanyaan itu yang hendak ia jawab dan uraikan secara jeli: latar belakang, signifikansi, serta tujuannya.
Ia menyimpulkan bahwa pintu belakang memiliki peran sentral sebagai wahana untuk meruntuhkan formalitas dan menyemai hubungan-hubungan emosional-kekerabatan. Suasana formal (penuh sopan-santun, kaku, dan lain-lain) yang dipegang teguh masyarakat Jawa terhadap tamu yang cenderung datang dari pintu depan dirasa perlu diberi alternatif melalui pintu belakang untuk meruntuhkan semua formalitas itu bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional-kekerabatan atau tak diposisikan sebagai tamu.
Dalam perkembangannya, sebagaimana terhadap tradisi atau bahkan kata lain yang sering terjadi reduksi hingga pemutarbalikan makna, terjadi pula pada “pintu belakang”. Ia dirusak filosofinya hingga bermakna konotatif, yakni jalur ilegal, wahana kasak-kusuk, dan lain-lain.
Dalam tradisi masyarakat muslim peranakan Hadhramaut (Yaman) di Nusantara atau yang biasa disebut muwallad dan kini populer dengan istilah “Sayyid”, “Habib”, dan lain-lain, “pintu belakang” juga bagian dari tradisi dan arsitektur rumah-rumah mereka. Bisa jadi ia bagian dari asimilasi dengan tradisi Jawa. Sebab, tulisan ini berangkat dari pengamatan atas sayyid di kawasan Jawa, tepatnya di daerah Bondowoso (Jawa Timur).
Namun, selain fungsi yang telah disebutkan sebagaimana ada dalam tradisi Jawa, ada fungsi tambahan dalam pintu belakang ala sayyid di Bondowoso. Ini tampaknya lantaran kuatnya doktrin Islam dalam masyarakat sayyid yang dibawa dari Hadhramaut.
Di Hadhramaut, sebagaimana diuraikan Hamid Ja’far Al-Qodri dalam “Kisah dan Hikmah Wanita Hadhramaut” (2017), wanita begitu dijaga dan menjaga secara ketat hijab-nya: interaksi dengan lelaki bukan muhrim. Bahkan, meskipun cadar (menutup wajah dan telapak tangan) menjadi perkara ikhtilaf (perbedaan pendapat) di antara ulama, di mana ada yang tak mewajibkannya dan ada pula yang mewajibkannya, wanita Hadhramaut memegang tradisi bercadar sebagai bagian dari iffah (harga diri).
Namun, bukan berarti mereka menjadi eksklusif: terkungkung di rumah, misalnya. Mereka juga memiliki aktivitas dan peran sosial. Misalnya belajar-mengajar dan beribadah bersama di luar rumah. Oleh karena itu, mereka memilih membangun sekolah dan rumah ibadah sendiri untuk sesama wanita. Letaknya ‘pun biasanya di gang-gang dan akses-akses relatif khusus agar tak berpapasan dengan kaum pria.
Ketika mereka berdiaspora ke Nusantara, ciri utama mereka adalah berakulturasi dengan masyarakat dan tradisi Nusantara. Namun, di sisi lain, mereka memegang teguh tradisi-tradisi tententu yang dinilai mendasar, terlebih yang berkaitan dengan doktrin Islam yang dalam tafsir mereka mendasar dan prinsipil.
Di tengah tantangan itu, sebagaimana dalam perkara-perkara lain, kalangan wanita Hadhramut (syarifah) merasa harus tetap menjaga iffah-nya, namun juga beraktivitas dan berperan secara sosial. Relatif sama dengan di Hadhramaut, mereka biasanya membangun atau memfungsikan sebagian rumah tokoh-tokoh mereka menjadi sekolah dan musholla khusus wanita. Letakkan ‘pun biasanya di belakang rumah dengan akses khusus. Termasuk juga bersambung ke kuburan karena mereka memagang teguh tradisi ziarah kubur.
Nah, akses khusus itulah yang kemudian tampaknya berasimilasi dengan tradisi “pintu belakang” dalam masyarakat Jawa. Pintu belakang ditambah fungsinya sebagai akses bagi para syarifah untuk tetap melakukan interaksi dan peran sosial di kalangan wanita di antara mereka. Oleh karena itu, setiap rumah para peranakan Hadhramaut di Nusantara dulu selalu memiliki pintu belakang. Bukan hanya itu, ditambah pula “jalan belakang”.
Di Bondowoso, jalan belakang itu membentang dari ujung barat ke timur “Kampung Arab” (kawasan berpenghuni kaum sayyid yang sebenarnya diciptakan oleh Belanda sebagai bagian dari agenda kolonialisme untuk mempersempit ruang gerak dan pengaruh sayyid atas masyarakat pribumi yang kala itu berprinsip bahwa Indonesia harus merdeka). Melalui jalan belakang yang bersambung ke pintu-pintu belakang di setiap rumah di Kampung Arab itulah kemudian para syarifah melakukan aktivitas sosial-keagamaan. Sehingga dengan begitu mereka bisa tetap menjaga hijab sebagai iffah-nya, namun juga bisa beraktivitas sosial-keagamaan secara koleksif (berjamaah) sehingga tumbuh dan berperan tanpa subordinasi.
Itulah fungsi tambahan pintu belakang dalam tradisi peranakan Hadhramut di Indonesia. Meskipun saat ini, jalan belakang itu sudah relatif tergerus oleh ambisi pembangunan. Namun, pintu belakangnya tetap eksis. Saat ini biasanya mereka berjalan melalui jalan depan dengan menutup wajahnya dan masuk melalui akses baru berupa gang (jalan kecil) di samping rumah yang bersambung ke pintu belakang. Tentu, ini menarik sebagai objek penelitian. (Husein Ja’far Al Hadar, Ketua Bidang Informasi dan Publikasi MAHYA)